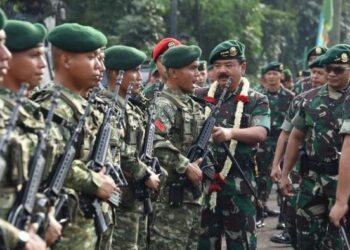Indonesia merupakan sebuah bangsa yang menganut paham pluralisme dan kebetulan faktanya demikian, bahwa mungkin yang paling plural di belahan dunia. Bangsa ini terdiri dari ratusan etnik, agama, budaya, dan adat istiadat, yang tinggal di sekitar 13.000 pulau baik besar maupun kecil. Serta berbicara dalam ratusan bahasa daerah.Pluralisme yang multidimensial ini telah membentuk Indonesia yang sangat indah dan sekaligus menjadi sangat rawan dengan konflik horizontal. Ketidakmampuan mengelola dengan baik pluralisme ini, akan bisa mendorong terjadinya gejolak-gejolak sosial politik yang bernuansa sparatis (Juhri, 2008: 560).
Indonesia sebagai potret bagi negara yang plural baik dari sudut pandang agama, suku bangsa, etnik, bahasa, dan adat istiadat yang masing-masing dapat beradaptasi secara wajar dengan lingkungan sosialnya. Karena itu pula Indonesia menjadi negara yang indah dan kaya dengan budaya masyarakat. Dalam hal agama misalnya, terdapat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan, mereka dapat bersatu membangun Indonesia yang indah.Kebersamaan dalam keberagaman ini merupakan ciri khas dari kebangunan Indonesia dan sekaligus sebagai rahmat dari Allah SWT untuk bangsa Indonesia. Persoalannya kemudian, ketika muncul provokasi dan hasutan terhadap massa agama, etnik atau suku tertentu terhadap yang lain oleh pihak yang mempunyai kepentingan tertentu, maka kebersamaan menjadi ancaman dan ancaman bagi keamanan bangsa secara keseluruhan. Keragaman yang kita miliki merupakan potensi konflik yang sangat menakutkan bagi eksistensi manusia.Karena itu peran kaum agamawan untuk menjadi panutan umat mereka, sehingga nilai-nilai moral agama itu tidak tercemar dan umat tidak mudah terprovokasi oleh hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Juhri, 2008: 561).
Maksum (2011:14) dalam buku multikulturalnya menyampaikan Ki Supriyoko (2004) melihat kemajemukan dan multikulturalisme bangsa ini mengisyaratkan keragaman.Keragaman ini merupakan modal sosial (sosial capital) yang sangat berharga. Bila dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi keuntungan besar bagi kejayaan bangsa ini. Tetapi juga sangat rentan terjadi konflik antar warga dan antar agama manakala tidak dikelola secara benar.Dalam konteks ini, kemajemukan dan multikulturalitas bisa menjadi faktor destruktif dan menimbulkan bencana dahsyat.Konflik dan kekerasan sosial yang sering terjadi antara kelompok masyarakat merupakan bagian dari kemajemukan dan multikulturalitas yang tidak bisa dikelola dengan baik.
Konflik dan kekerasan sosial merupakan masalah penting ditengah realitas sosio kultural Indonesia sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah pra-kemerdekaan Indonesia hingga hari ini, kehidupan bangsa Indonesia penuh diwarnai instabilitas sosial politik dan konflik yang berujung pada terjadinya tindak kekerasan. Kekerasan di Indonesia ibarat mati satu tumbuh seribu, merangkai perspektif dulu dan perspektif kini salah satu deskripsi Indonesia kontemporer yang diwarnai kekerasan, inilah sebuah konsekuensi kalau potensi multikuturalisme tidak terkelola dengan baik maka sudah pasti akan menjadi bencana yang menakutkan (Maksum, 2011: 14).
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa praktik kekerasan telah dilaksanakan secara merata oleh masing-masing generasi dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Realitas kekerasan etnik agama hingga kini terus berlangsung di bumi Indonesia, seperti konflik Sambas, Sampit, Maluku, Poso, Ambon, dan gejolak sosial di Aceh dan Papua, serta masih banyak lagi. Hal itu menunjukan betapa rapuhnya konstruksi kebangsaaan berbasis multikultural di Indonesia (Maksum, 2011: 14)
Dari uraian di atas,, sesungguhnya kekerasan merupakan masalah sosio kultural besar dan penting bagi bangsa Indonesia yang semata-mata tidak bersifat aktual namun juga bersifat menyejarah. Sifat realitas kekerasan dan konflik sosial tersebut membenarkan anggapan bahwa kekerasan hampir menjadi mind-set kolektif maupun individual bangsa Indonesia. Tantangan dalam pengelolaan multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab besar yang bukan hanya ditanggung oleh para pemuka agama tetapi oleh semua pihak yang terkait dengan hal tersebut, sehingga keindahan dalam multikulturalisme bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang pada kenyataannya sangat beragam.
Rendahnya kesadaran multikultural ditengah kehidupan ummat manusia, bukan semata masalah domestik Indonesia, melainkan juga masalah global. Brenes dan Wessells mengemukakan betapa kekerasan sistematik menantang ummat manusia untuk menumbuhkembangkan budaya perdamaian berlandaskan hak asasi manusia (HAM), persamaan, kebebasan, tenggang rasa, solidaritas, dan perlindungan terhadap sumberdaya bumi (Maksum, 2011: 15).
Di lain pihak, Juhri (2008:557) memandang pluralisme agama ataupun pluralitas masyarakat tidak dapat dipahami hanya dengan kita mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah potret masyarakat yang majemuk,masyarakat yang heterogen atau beranekaragam, dengan berbagai suku bangsa, etnik yang beragam, agama dan munculnya aliran kepercayaan yang berbeda, tetapi bagaimana memahami pluralisme dalam konteks yang religius, politis dan tidak membuat kesan yang justru menggambarkan fragmentasi, sehingga pluralisme sebagai realitas yang hidup dalam masyarakat hanya dipahami sebagai bentuk lain dari kebaikan yang hanya dilihat dari sudut pandang kegunaannya untuk menyingkirkan bentuk fanatisme sempit. Pluralisme dalam konteks keagamaan harus dipahami sebagai pertalian sejati keragaman atau kemajemukan dalam ikatan sosial, budaya atau keadaban dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, konsep pluralisme menjadi faktor positif dan bermakna kebaikan yang menebarkan kedamaian dan kasih sayang dan bukan sebagai bentuk yang menakutkan, melahirkan konflik dan kekerasan, melainkan faktor pendukung bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia dalam Al-Quran QS. Al-Hujurat (49): 13, “Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.Oleh karena itu, pluralisme harus dipandang dari sisi positifnya dan bukan sebagai faktor yang disintegratif bagi masyarakat (Juhri, 557: 2008).
Ayat di atas cukup menjelaskan bahwa kenyataan penciptaan manusia itu sendiri dalam kenyataan beragam sehingga peran dan komitmen yang harus dipegang oleh umat beragama yang hidup di atas pluralitas seperti Indonesia adalah saling menghormati dan menghargai masing-masing pihak dalam kehidupan bermasyarakat, antara berbagai komunitas agama yang eksis dan tidak ada satu agama pun yang memaksakan keyakinannya kepada umat yang telah beragama. Islam misalnya, dalam kitab sucinya menyebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi. Disebutkan oleh Allah “Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur, namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam “.Ayat ini memberikan penegasan mengenai kemahakuasaan Allah terhadap manusia bahwa Allah telah menciptakan keseimbangan diantara speciesatau jenis yang berada di Bumi (Juhri, 2008: 558).
Ayat di atas mengandung pesan tentang pluralisme yang merupakan salah satu permasalahan yang menyulut pada perdebatan abadi, berkaitan dengan konsep keselamatan kehidupan manusia baik di bumi maupun keselamatan untuk menuju surga-Nya di akhirat nanti. John Lyden mengatakan, “apa yang orang pikirkan mengenai agama lain, dibandingkan agama sendiri?”,artinya keyakinan yang dimilikinya mengandung pesan yang baik bila dibandingkan dengan keyakinan lain. Pluralisme semacam ini tidak harus diakhiri dengan konflik dan kekerasan, tetapi dibungkus dalam bingkai toleransi agama-agama.Keharusan untuk melakukan pertemuan baik secara pribadi maupun dalam suatu komunitas, guna membicarakan masalah umat beragama dan bukan dalam kerangka agama melainkan dalam kerangka kemanusiaan, karena keyakinan agama yang hidup di
atas pluralisme menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan.Sementara itu,ritual keagamaan tetap tidak bisa disatukan dalam pertemuan atau forum apa pun karena dasar keyakinan mengenai bentuk penyembahan kepada Tuhan telah berbeda secara fundamental. Kesediaan semua pihak (kalangan agama) untuk membiarkan pihak lain melaksanakan kewajiban agamanya merupakan langkah bijak dan arif untuk membangun suasana keberagaman yang akrab, penuh toleransi dengan selalu melibatkan diri dalam berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat (Juhri, 2008:559).
Dalam faktanya, konflik yang terjadi dimasyarakat kita banyak dipengaruhi dan dipicu oleh faktor keragaman budaya, adat, agama dan etnik. Beberapa faktor penyebab hal ini diantaranya, Pertama lebih disebabkan oleh provokasi dan propaganda pihak-pihak tertentu terhadap massa agama agar mereka melakukan kekerasan terhadap agama yang lain. Kedua disebabkan oleh gengsi, merasa etniknyalah yang paling super, paling baik sehingga ketika ada etnik lain yang menyainginya, maka tidak akan senang dan menimbulkan kekerasan massal yang justru tidak mampu dijelaskan dalam kerangka kehidupan sosial, budaya, politik-keduanya masih tetap akan eksis dalam masyarakat.
Dalam pandangan Husaini (2005), pluralisme merupakan istilah yang memberikan janji penuh tentang kehidupan damai dan rukun antarmasyarakat yang berbeda terutama agama. Di Indonesia, sistem dan ideologi pluralisme bisa tumbuh dengan cepat, di bumi Indonesia yang mengamalkan pranata Nation State. Dalam faktanya, pluralisme dianggap sebagai dewa penyelamat dan pemersatu bangsa, sehingga harus dipelihara, dibela dan dipertahankan sedemikian rupa, bahkan melalui lembaga konstitusi Negara dengan sederet undang-undang dan peraturan pemerintah pada UU No.8/1985 (tentang asas tunggal).
Husaini (2005, xiv) memandang, kedepan pekerjaan yang lebih serius dalam melawan penyebaran paham pluralisme agama, liberalisme dan sekulerisme adalah dengan menyiapkan sebanyak mungkin cendikiawan dan ulama Islam yang mumpuni dan mendirikan kampus Islam yang baik dan berkualitas tinggi, sebagai percontohan dalam membangun sistem pendidikan tinggi Islami. Sebab inti dari semua masalah ini adalah kekeliruan cara berfikir, kerancuan konsep ilmu dan pertarungan hidup mati antara yang haq dan batil.
Melihat tulisan Husaini dalam beberapa buku, pemikirannya menentang habis yang namanya pluralisme agama. Dari data diatas, Husaini melihat bahwa faham pluralisme agama lebih pada kerancuan berfikir, kerancuan konsep ilmu dan sampai pada tingkatan pertarungan antara yang hak dan batil. Sebenarnya Husaini menolak konsep pluralisme ketika pluralisme itu menyangkut aqidah yang mencampuradukan dan menyamaratakan semua agama. Hal ini bisa kita lihat dalam pandangan Husaini menyikapi fatwa MUI tentang pluralisme agama yang banyak ditentang oleh berbagai pihak dalam yang merasa tersinggung dengan sikap MUI tersebut terutama dari kalangan yang mendukung paham pluralisme.Husaini memandang Fatwa MUI tentang pluralisme agama sudah tepat, meskipun sebenarnya terlambat. Sebab paham ini sudah sedemikian lama dikembangkan dengan dukungan dan fasilitas luar biasa, sehingga penyebarannya juga bersifat massif dan infiltratif. Lihat saja meskipun MUI sudah mengharamkan paham ini, tetap saja ada tokoh yang menyebarkannya.
Husaini mencontohkan artikel Tarmizi Taher dialog Jum‟at Republika, yang berjudul “Agama dan Konflik” secara terang-terangan menghimbau kaum muslimin untuk memeluk paham syirik ini. Ditulis “Pluralisme agama sebagai salah satu unsur terpenting demokrasi harus menjadi fokus utama semua orang. Jika selama ini pluralisme belum terpahamkan lewat dialog, maka harus ada sosialisasi lewat media publik, seperti kampanye, pemutaran film, penerbitan buletin ke pedesaan, kelompok kajian, partai politik dan lain-lain, Menyikapi hal tersebut, Husaini (2005: 19) berpendapat mungkin Tarmizi Taher sendiri tidak paham dan tidak sadar akan makna pluralisme agama. Tapi tulisan Tarmizi Taher ini dapat diambil sebagai kasus yang menggambarkan bagaimana orang yang selama ini dikenal sebagai “bukan tokoh liberal” pun turut menyebarkan paham destruktif terhadap akidah Islamiyah ini, meskipun sudah ada Fatwa MUI yang mengharamkannya.
Berbeda dengan Husaini, Raharjo dalam tulisannya sebagiamana dikutip dari Rahman menyampaikan bahwa:
“Pada dasarnya liberalisasi pemikiran adalah konsekwensi dari pluralsme masyarakat moderen yang makin kompleks yang mendorong keterbukaan komunikassi antar warga masyarakat.Sebenarnya komunitas madinah pada zaman nabi sendiri lahir dari suatu masyarakat yang plural. Beliau menyampaikan tanpa masyarakat yang plural ini tidak akan lahir piagam madinah yang menjadi konstitusi masyarakat madinah pada waktu itu. Pada waktu piagam madinah dirumuskan dan disetujui, komunitas Islam masih merupakan minoritas, komunitas terbesar adalah komunitas Yahudi ditambah dengan komuntas Kristen dan penganut Kepercayaan Pagan. Justru dalam masyarakat yang plural itu, nabi berperan sebagai pemersatu, tanpa melebur kedalam suatu masyarakat yang tunggal. Dalam kesepakatan yang plural itu diproklamasikan terbentuknya “Masyarakat yang satu” (Ummatan Wahidah). Namun dalam konstitusi yang merupakan kontrak sosial itu, identitas kelompok tetap diakui. Itulah hakekat pluralisme yang merupakan reaktualisasi pluralisme dizaman klasik Islam. (Rahman, 2010: XLIX).”
Rahman (2010: XLIX) ingin menyampaikan pesan yang disampaikan Raharjo, bahwa pluralisme dalam Islam bukan hal yang baru, sehingga dalam kutipan diatas disampaikan bagaimana hakekat dari pluralisme agama sudah ada sejak zaman Rasul bahkan diawal pendirian Negara Madinah yang menjadi titik tolak kebangkitan Islam. Budhy dan Raharjo ingin menyampaikan bahwa pluralisme memang diajarkan dalam ajaran Islam sebagaimana peran Rasul dalam mempersatukan komunitas yang berbeda agama di Madinah sehingga mereka bisa hidup rukun dan berdampingan. Menurut Raharjo “ Dunia Islam, sejak awal perkembangannya sudah merupakan pluralitas dan karena itu mendekatnya dengan pluralisme yang merayakan keragaman sebagai rahmat. Dalam menghadapai realitas dunia Islam itulah berkembang pluralisme dalam Islam”. Dalam hubungannya dengan kondisi Indonesia yang dalam kenyataannya sangat beragam dan plural, nampaknya Raharjo menganalogikan bagaimana pembentukan negara yang digagas oleh Rasulullah diatas pluralitas sehingga menjadi sebuah bangunan negara yang kokoh.
Rahman (2010: L) mengutip pernyataan Raharjo menyampaikan beberapa alasan kenapa paham pluralisme agama itu ditolak. Pertama, sementara pluralitas diakui sunnatullah, pluralisme dianggap sebagai ancaman yaitu ancaman terhadap akidah. Pengakuan terhadap pluralisme dianggap akan melemahkan iman. Kedua, Pluralisme juga dianggap sebagai ancaman terhadap identitas, sebab dalam pluralisme identitas akan lebih kedalam monolitas masyarakat. Dasar pemikirannya adalah dalam pluralitas, kebenaran mutlak akan digantikan oleh kebenaran relatif. Kebenaran tidak lagi tunggal melainkan plural. Padahal ummat Islam berpedoman kepada Al-Qur‟an bahwa “ Agama yang diakui Allah adalah Islam”. Ketiga, Ancaman terhadap eksistensi agama akan timbul dengan diakuinya kebenaran semua agama. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi singkretisme agama yang akan melahirkan agama publik yang meramu ajaran semua agama.
Selain hal di atas, Rahman mengutip pernyatan Raharjo juga memberikan pandangan tentang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2005 tentang larangan pluralisme agama :
Pluralisme sebagai paham, ini agaknya tidak di pahami oleh MUI. Otoritas keagamaan ini membedakan antara pluralitas dan pluralisme, menurut persepsi MUI dan beberapa pendukungnya yang umumnya adalah kelompok Islam garis keras.Pertama: Pluralisme khususnya pluralisme agama sebenarnya bersumber dari teologi kristen. Kedua: Dibalik pluralisme itu tersembunyi kepentingan politik dan ekonomi dari negara-negara adikuasa barat”. Raharjo juga menyampakan pendapat Nurkholis Madjid bahwa “ Islam disitu adalah kata generik, yang artinya adalah berserah diri kepada Tuhan”, karena itu agama yang diridhoi Allah adaah agama yang berserah diri kepada Allah. Buktinya agama- agama yang di ajarkan oleh para nabi, termasuk nabi-nabi yahudi adalah juga Islam, karena inti ajarannya dalah berserah diri kepada Allah (Rahman, 2010: LII).
Dari pandangan Raharjo, Munawar dan Husaini yang bertentangan dalam cara pandang terhadap pluralisme agama, menurut hemat penulis masih adanya perbedaan pemahaman antara tokoh-tokoh ini, sehingga dalam menyikapi kenyataan keberagaman yang ada di Indonesia tokoh tersebut saling berbeda. Diawal tulisan ini, disampaikan bahwa keragaman ini akan menjadi rahmat apabila bisa dikelola dengan baik dan bisa mengambil hal positif dari keragaman tersebut, tapi bila keragaman yang ada di Indonesia tidak bisa dikelola dengan baik oleh masyarakatnya sendiri yang ternyata beragam etnis, agama, adat istiadat sudah barang tentu akan menjadikan sebuah ancaman tersendiri terhadap nilai kesatuan atau kerukunan yang ada.
Di Indonesia, tanpa pluralisme atau Bhineka Tunggal Ika akan timbul ancaman terhadap kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika sebagian kelompok ummat Islam garis keras mengancam rumah ibadah-rumah ibadah ummat Kristen untuk ditutup, mereka merasa hak-hak asasi mereka telah dicabut dengan paksa sehingga timbul suara-suara yang menuntut suatu wilayah yang disediakan dengan khusus dihuni oleh ummat Kristen dan terbebas dari kediktatoran mayoritas ummat Islam. Sementara itu diberbagai tempat telah timbul konflik yang diidentifikasi sebagai konflik antar penganut agama yang berbeda (Rahman, 2010: LVI).
Disisi lain, Muhaimin dalam sambutan buku Ali Maksum (XIII) menyampaikan bahwa fenomena yang paling menonjol di Indonesia di era reformasi adalah kekerasan antara kelompok agama. Berbagai catatan akhir dan awal tahun oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menekuni bidang hak asasi manusia, kebebasan beragama dan keyakinan menunjukan keprihatinan yang mendalam serta deretan catatan tentang arus pasang kelompok agama.
Muhaimin menganalisis bahwa dalam kasus kekerasan seperti di atas ada beberapa dimensi yang bisa berperan disana. Pertama, dimensi agama yang bisa di perankan oleh MUI dan ORMAS islam dalam membentuk persepsi masyarakat. Kedua, dimensi negara yang diperankan oleh aparat keamanan dan hukum yang harus mampu memberikan keamanan dan perlindungan kepada korban. Ketiga, civilsociety yang diperankan para pelaku kekerasan yang secara sosial mestinya memiliki batas-batas solidaritas dan toleransi tertentu yang dibutuhkan jika masing-masing hal tersebut diluaskan dimensinya maka aparat negara bisa diikutkan didalamnya, berbagai peraturan dan perundang-undangan yang tidak mendukung atau bahkan cenderung bertentangan dengan konstitusi negara yang mengancam harmoni antar kelompok masyarakat di Indonesia yang Berbineka Tunggal Ika (Maksum, 2011: XIV).
Dalam menyikapi hal diatas, Muahimin lebih menyoroti pada aspek pendidikan, dimana konflik yang terjadi seperti diatas bisa diantisipasi melalui pendidikan. Muhaimin menegaskan bahwa sangat mendesak untuk membumikan pendidikan islam berwawasan pluralisme dan multikulturalisme. Kesadaran akan pentingnya pluralisme dan multikulturalisme dipandang bisa menjadi perekat baru integrasi bangsa yang sekian lama tercabik-cabik. Integrasi nasional yang selama ini dibangun dengan politik kebudayaan lebih cenderung seragam dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi dan semangat demokrasi global. Desentralisasi kekuasaan dalam bentuk otonomi daerah sejak tahun 1999 adalah jawaban bagi tuntutan demokrasi tersebut,namun desentralisasi sebagai keputusan politik nasional ternyata kemudian disadari tidak begitu produktif apabila dilihat dari kacamata integrasi nasional suatu bangsa besar yang isinya beraneka ragam suku bangsa, etnis, agama dan status sosial.Secara ontologis, multikulturalisme dan pluralisme itu menjadi penguat etis bagi peneguhan sikap keberagaman yang lebih inklusif terbuka dan toleran. Oleh karena itu, perlu dipahami sentimen keagamaan sering dibangun oleh agamawan yang gencar menerapkan politik reprentasi secara terus menerus (Maksum, 2011: XV).
Menyinggung peranan pluralisme dalam berbangsa dan bernegara,Raharjo berpendapat pluralisme sudah menjadi ideologi nasional yang dirumuskan dengan istilah “Bhineka Tunggal Ika”, suatu istilah yang berasal dari Empu Tantular, yang artinya kesatuan dalam keragaman. Pluralisme juga tercermin dalam pancasila yang terdiri dari berbagai ideologi besar dunia tetapi intinya adalah faham kegotong royongan, kekeluargaan dan kebersamaan (Rahman, 2010: LII). Selain itu, anggapan bahwa semua agama itu baik dan benar adalah sikap yang dituntut terhadap negara. Menggangap bahwa hanya satu agama saja yang benar dimata pemerintah atau negara akan menimbulkan favoritisme disatu pihak dan diskriminasi dilain pihak. Padahal negara dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana karena itu pandangan yang harus diadopsi oleh setiap negara adalah seperti ditegaskan oleh Budhy yang memandang bahwa semua agama itu baik dan benar (Rahman, 2010: LIV).
Raharjo berpendapat sebagaimana disampaikan Rahman (2010: LIV) bahwa “ menyamakan semua agama itu lebih merupakan sikap negara yang harus adil dan bukan lagi suatu pandangan apalagi kepercayaan”. Oleh karena itu, sikap itu bukan merupakan sikap dari akidah, melainkan hanyalah suatu kebijakan negara dalam kebijakan itu setiap pemeluk agama masih terus bisa menganggap agamanya yang benar. Tapi sikap ini tidak perlu dinyatakan secara terbuka karena arahnya ke dalam kepada iman dan individual.
Di Indonesia tanpa pluralisme atau Bhineka Tunggal Ika akan timbul ancaman terhadap kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika sebagian kelompok ummat Islam garis keras mengancam rumah ibadah ummat Kristen untuk ditutup, mereka merasa hak-hak asasi mereka telah dicabut dengan paksa sehingga timbul suara-suara yang menuntut suatu wilayah yang disediakan dengan khusus dihuni oleh ummat Kristen dan terbebas dari kediktatoran mayoritas ummat Islam. Sementara itu diberbagai tempat telah timbul konflik yang diidentifikasi sebagai konflik antar penganut agama.